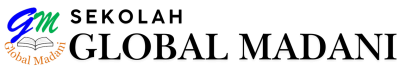Di era modern yang serba canggih ini, teknologi kian menembus batas imajinasi manusia. Segalanya dapat disentuh hanya dengan ujung jari. Dalam derasnya arus digital dan informasi yang mengalir tanpa henti, kemampuan berliterasi bukan lagi sekadar keterampilan pelengkap, namun nafas utama kehidupan intelektual manusia. Literasi bukan semata kemampuan membaca deretan kata dan merangkai kalimat, melainkan kecakapan menyelami makna, mengolah gagasan, serta menata nalar hingga menghasilkan tindakan yang bijaksana. Di sanalah literasi menjelma sebagai lentera yang menerangi langkah kita di tengah kabut informasi yang kian pekat dan menyesatkan arah.
Sebagai guru Bahasa Indonesia, saya kerap merenung. Mengapa generasi muda kini begitu cepat menggulir layar ponsel, namun kerap sulit menggulir lembaran buku? Mengapa lebih mudah memahami isi video berdurasi enam puluh detik, tetapi seperti kehilangan arah ketika dihadapkan pada satu paragraf bacaan yang menuntut pemikiran? Ternyata jawabannya sederhana, bukan karena kita tak mampu, namun karena kita belum terbiasa menikmati proses membaca dengan hati.
Membangun budaya literasi sejatinya bukan perkara menumpuk banyak buku di rak, tetapi tentang tumbuhnya kesadaran untuk terus belajar, berpikir kritis, dan berempati melalui kata. Menyadarkan diri bahwa membaca adalah jendela menuju dunia yang lebih luas tak terbatas, dan menulis adalah cara untuk merekam jejak pikir dan denyut rasa, agar apa yang lahir dari benak tidak hilang ditelan waktu. Literasi adalah titik temu antara rasa ingin tahu dan dahaga makna dalam memahami kehidupan.
Hal krusial yang mesti kita pahami adalah bacaan yang baik tak selalu harus berat. Ada kalanya seuntai kisah sederhana bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Namun sangat disayangkan, banyak orang membaca hanya untuk menyelesaikan halaman, bukan untuk menemukan makna. Membaca dengan jiwa berarti hadir sepenuhnya dalam setiap rangkaian kata, menanyakan, menafsirkan, dan merasakan.
Sebagai guru, saya sering mengajak siswa membaca dengan strategi reflektif. Dengan sengaja mengajak mereka berhenti di tengah teks, lalu bertanya, “Apa makna kalimat ini bagimu?” atau “Jika kamu berada di posisi tokoh ini, apa yang akan kamu lakukan?” Dari pertanyaan sederhana ini, teks tak lagi terasa asing, ia hidup berdialog dengan pembacanya.
Sering kali kita mendengar pepatah lama yang tak lekang oleh waktu, “Membaca buku adalah membuka jendela dunia.” Maka dengan menulis bukan sekadar merangkai kata, melainkan menata batin dan menyingkap cakrawala pikiran. Melalui tulisan, kita belajar menata nalar dengan runtut, menajamkan pikiran, serta mengasah kepekaan nurani terhadap makna kehidupan.
Setiap kalimat yang lahir dalam tulisan kita bukan hanya untaian bahasa, tetapi jejak yang telah melewati proses penjernihan pikiran, pengendapan gagasan, dan perenungan makna yang mendalam. Tulislah, meski hanya satu paragraf sehari. Karena tulisan hari ini bisa menjadi bukti bahwa kita pernah berpikir. Tidak ada tulisan yang sia-sia, sebab setiap kata menyimpan energi yang mampu menggerakkan hati pembacanya. Menulis juga mengajarkan kerendahan hati. Kita belajar menerima koreksi, menimbang diksi, dan memperhalus makna.
Hal yang tak kalah esensial, literasi digital menuntut kita untuk cermat menapaki arus informasi. Memilah yang benar dari yang bias, menakar kredibilitas sumber dengan nalar yang kritis, serta menahan jemari sebelum turut menyebarluaskan informasi. Di tengah derasnya hoaks, literasi digital adalah tameng paling ampuh.
Saya kerap mencontohkan hal-hal kecil yang sarat makna kepada murid-murid saya: “Jangan cepat percaya pada judul berita. Baca isi, perhatikan tanggal, dan telusuri sumbernya.” Dari kebiasaan kecil ini, kita belajar bahwa membaca di dunia mayapun membutuhkan tanggung jawab moral, kebijaksanaan, dan ketelitian.
Literasi bukan tumbuh dari paksaan, melainkan dari kebiasaan kecil yang diulang dengan cinta dan konsisten. Mengajak anak membaca buku, berbincang tentang isi bacaan, mengulas kembali tentang buku bacaan yang sedang atau telah selesai dibaca, menulis jurnal harian, membuat pojok baca sederhana, atau membacakan cerita sebelum tidurpun adalah langkah kecil yang bermakna besar.
Tugas seorang guru Bahasa Indonesia, sejatinya bukan hanya mengajarkan ejaan, struktur kalimat, atau tanda baca. Melainkan memikul amanah untuk menyalakan lentera di dada para murid. Menuntun mereka agar mampu berpikir jernih, bertutur dengan santun, dan menulis dengan makna. Sebab di balik setiap huruf yang diajarkan, tersimpan upaya menumbuhkan manusia yang berbahasa sekaligus berbudaya.
Ketika literasi telah menjadi bagian dari gaya hidup, kita tak lagi membaca karena tugas, tetapi karena kebutuhan. Saat itu, buku bukan lagi benda mati yang berdebu di rak, melainkan sahabat yang setia membuka cakrawala.
Writer: Fika Oktafia, S.Pd., Gr.
Editor: Ririn Tria Piani, M.Pd., Gr.