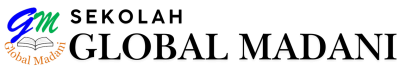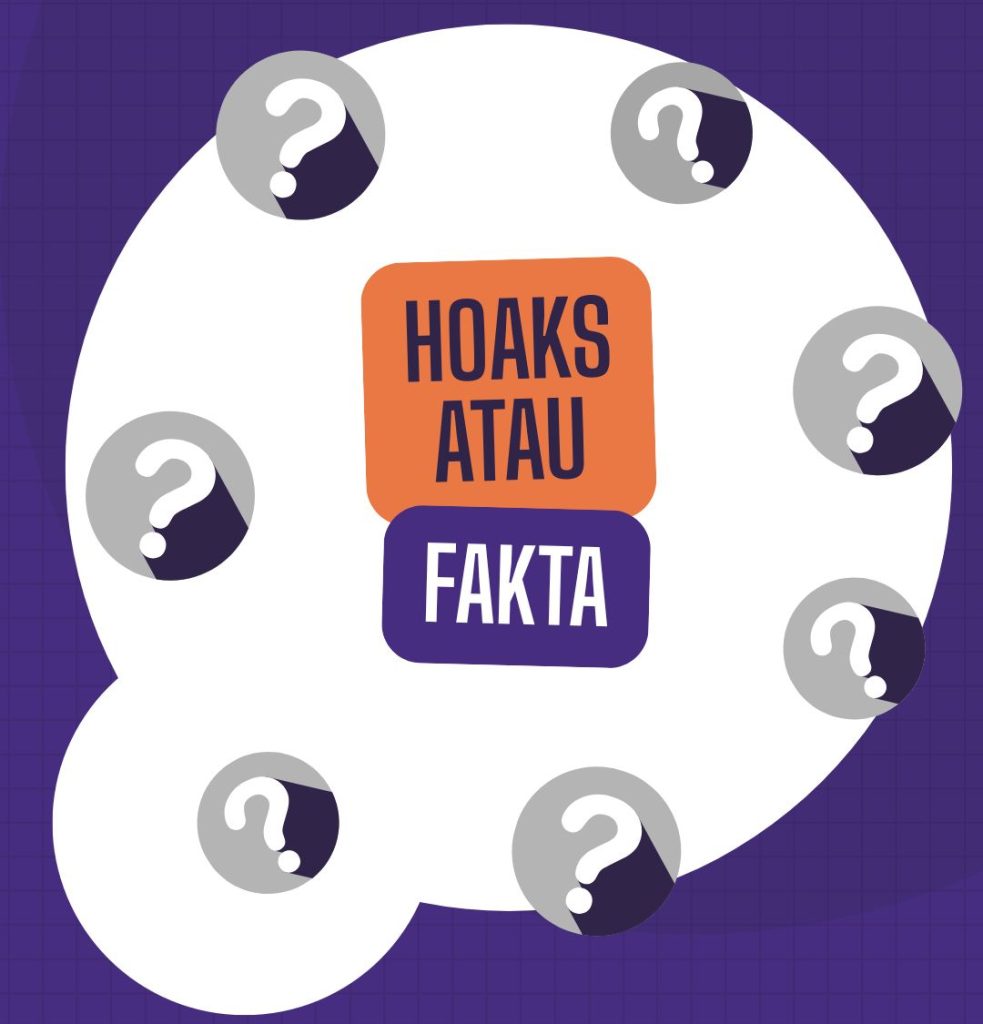Media sosial kini menjadi pintu utama siswa memperoleh informasi. Laporan Reuters Institute 2025 mencatat bahwa 57% masyarakat Indonesia menggunakan media sosial untuk mencari berita, dan 40% menjadikannya sebagai sumber utama. Angka ini bahkan lebih tinggi pada kelompok usia 18–24 tahun (The Jakarta Post, 2025). Fenomena ini membawa tantangan besar di ruang kelas: siswa semakin rentan menyerap informasi yang belum tervalidasi, termasuk hoaks dan konten viral yang menyesatkan.
Teori news literacy (literasi berita) menekankan pentingnya membekali siswa dengan kemampuan membedakan antara berita, opini, dan iklan, serta mendeteksi disinformasi sejak dini. Namun, survei terbaru menunjukkan hanya sepertiga masyarakat Indonesia yang pernah mendapatkan pendidikan literasi berita, menandakan masih lemahnya kesadaran kritis di masyarakat (The Jakarta Post, 2025). Untuk menjawab kebutuhan itu, praktik literasi digital di sekolah dapat mengadopsi strategi seperti SIFT (Stop, Investigate, Find, Trace), sebagaimana mulai diterapkan di Amerika Serikat untuk melatih kemampuan siswa mengenali konten yang kredibel (Teen Vogue, 2025).
Dalam konteks ini, guru memegang peran yang sangat krusial. Guru bukan hanya pengajar materi akademik, tetapi juga fasilitator berpikir kritis yang mengajak siswa menelaah berita viral dengan pertanyaan sederhana namun mendasar: “Apakah berita ini valid?”, “Dari mana sumbernya?”, atau “Mengapa bisa viral?”. Pembiasaan ini penting, sebagaimana disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika: guru dan siswa perlu bertindak cerdas—“cek dan ricek” sebelum percaya, dan jika informasi tidak valid, cukup “stop di jarimu” (Medcom.id, 2024).
Selain aspek kognitif, guru juga perlu memperhatikan aspek emosional. Berita-berita negatif di media sosial, terutama yang berhubungan dengan isu global, sering kali memicu kecemasan dan tekanan psikologis pada siswa. Pendekatan positive education yang berkembang di Australia relevan diterapkan untuk membekali siswa dengan keterampilan resiliensi emosional. Dengan demikian, mereka tidak hanya cerdas secara informasi, tetapi juga mampu mengelola dampak psikologis dari arus informasi yang tidak terbendung (Daily Telegraph, 2025).
Singkatnya, ketika kelas formal bersinggungan dengan “kelas media sosial”, guru memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kecerdasan media. Guru tidak sekadar menjadi penyaring informasi, melainkan penuntun agar siswa mampu bersikap kritis, sehat, dan bijak. Dengan begitu, berita di media sosial tidak menjadi bumerang emosional, melainkan kesempatan emas untuk melatih kemampuan berpikir kritis generasi muda.
Daftar Pustaka
- The Jakarta Post. (2025, 15 Juni). Social media dominates Indonesians’ news consumption. Diakses dari https://www.thejakartapost.com
- Teen Vogue. (2025, 3 Mei). Media literacy in schools is on the rise as teachers grapple with misinformation and conspiracy theories. Diakses dari https://www.teenvogue.com
- Medcom.id. (2024, 22 Oktober). Guru dan siswa bisa lakukan ini buat tangkal hoaks di dunia pendidikan. Diakses dari https://www.medcom.id
- Daily Telegraph. (2025, 10 Januari). Positive education explained: American movement finds new home in Aussie schools. Diakses dari https://www.dailytelegraph.com.au
Writer: Renita Prahastiani, S.Pd., Gr,
Editor: Rofi’ Darojat, Lc., MH., Gr.